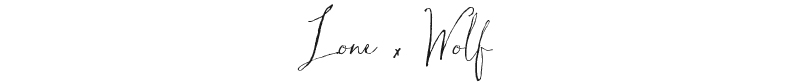Salahkan Armie Hammer. Dari dulu juga saya tahu dia cakep, tapi tiap lihat dia dulu kok kayaknya biasa aja. Just another pretty face, pikir saya. Sampai akhirnya liat trailer Call Me By Your Name… Nah, berhubung saya suka buku dan filmnya, dan malah keduluan Khara nulis review-nya, saya jadi pengen nulis semacam review-nya juga nih, mulai dari buku, filmnya, lanjut ke bukunya lagi. Haha. Here we go!
Karena urusan kerjaan, setiap harinya saya baca banyak artikel. Waktu itu sudah hampir award season, dan ada banyak banget artikel yang memperkirakan CMBYN bakal menang banyak. Saking seringnya lihat tuh judul film, saya pun penasaran dan langsung cari trailer-nya di YouTube. Tahu nggak rasanya lihat trailer dan langsung bisa nebak kalau filmnya bakalan bagus? Ya kaaan, kalau trailer filmnya aja malesin, gimana mau nonton? Setting tempatnya bagus dan dari trailer pun belum terlalu ketebak jalan ceritanya. Walaupun sempet negative thinking kalau salah satu karakternya bakalan mati. Ehe. Saya lihat trailer itu berkali-kali dan bertekad akan nonton filmnya. Via online streaming tentunya karena percuma nunggu film macam ini tayang di Indonesia. Kecuali kalau tiba-tiba menang Best Picture Oscar tuh kayak 12 Years A Slave atau The Shape of Water.
Terus, saya tahu dari artikel lain kalau film ini diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya André Aciman yang dirilis tahun 2007. Sebisa mungkin saya lebih suka membaca dulu bukunya sebelum nonton film yang diadaptasi dari buku itu. Iseng cari versi EPUB dan langsung ketemu! Huehe. Malam itu juga dalam perjalanan pulang di kereta saya mulai baca. Kayaknya saya sempet bikin thread di Twitter selama baca deh. *ubek Twitter* Ah, ini dia.
Sooo now I’m gonna read ‘Call Me by Your Name’ before I watch the movie even though I can’t wait to see it. 👀— 𝚍𝚒𝚊𝚑🥀 (@didigates) January 5, 2018
E ini kok nggak muncul thread-nya. Hahaha yaudah tinggal klik kalo kepo yaaak...
Oke, bahas bukunya dulu. Sempet mau baca ulang bukunya sebelum nulis ini, tapi kayaknya kelamaan yak. Jadi, berdasarkan yang saya ingat dan rasakan (tsah) pas baca aja ya… Udah nggak segreget kayak waktu bener-bener selesai baca sih.
Karena diceritakan dari sudut pandangnya Elio, kita jadi tahu pemikirannya Elio yang paling dalam, sampai ke fantasi dan pikiran mesumnya soal Oliver. Dia mencoba menelaah, sejak kapan sih gue jadi suka Oliver dan sejak kapan dia jadi sangat berarti buat gue? Sejak pertama kali menyapa? Sejak dia entah sengaja atau nggak, kulit mereka bersentuhan? Sejak sadar kalau omongan kalian nyambung dengan begitu mudahnya? Atau sejak pertama kali lihat dia dengan kemeja birunya? Kalau saya sih sejak album Coexist… OH BEDA OLIVER. Yah mulai jayus padahal baru mulai review. Mohon maaf.
Nah, menurut saya ini relatable banget sih. Entah karena udah terbawa perasaan atau gimana, kadang saya lupa atau nggak peduli sejak kapan sebenarnya suka sama seseorang. Tapi pernah tiba-tiba kepikiran gitu. Sejak kapan dan kenapa sih bisa suka sama nih orang? Padahal mah ngobrol juga nggak… cuma mengagumi dari kejauhan. Elio juga ngerasa nggak mungkin banget Oliver bakal membalas perasaannya, walau sejak awal udah menangkap sinyal-sinyal yang berbeda dan malah bikin tambah bingung. Sampai akhirnya makin yakin kalau Oliver juga flirting ke dia. Salah satu adegan yang bikin berkata, “NAH!” adalah waktu Oliver mijat bahunya Elio waktu break main voli. Oliver mau memastikan responsnya Elio. Sementara bagi Elio, ketahuan sudah. Dia speechless dan dia sadar ketidakmampuannya berkata-kata itu mengungkapkan kelemahannya.
Walaupun pinter dan jauh lebih dewasa dari umurnya, Elio tetep aja bocah waktu pertama kali ngerasain jatuh cinta. Ya indahnya, ya tersiksanya. Tau kan rasanya berandai-andai kalau orang itu bakal membalas perasaan kita juga, berusaha bertindak, terus ketika orangnya menghilang atau pergi sama yang lain gedek sampai bertanya-tanya sendiri, ‘Kenapa sih harus kenal sama dia dan bikin ngerasa tersiksa gini?’ Bahkan, ketika akhirnya mereka udah bersama, Elio masih ngerasa harus meyakinkan dirinya sendiri mengenai apa yang sebenarnya dia mau. Sampai akhirnya Elio sadar mereka nggak mungkin menjalin hubungan yang lebih dari itu. So, he settled for less and start counting the days.
"Are you saying what I think you're saying?"
Sementara di filmnya…
Pikiran Elio nggak dituangkan ke dalam narasi, melainkan dari curi-curi pandang dan gestur yang dimainkan dengan apik oleh Timothée dan Armie. Membangun ketegangannya juga cukup dari gestur dan dialog aja. Kalau menurut saya di bukunya lebih fisik sih, ada adegan mereka tempel-tempelan kaki di bawah meja makan gitu deh... Waktu pertama nonton saya sempet mikir, Ini nanti yang nggak baca bukunya bakalan bingung deh kayaknya kenapa mereka bisa saling jatuh hati. Apalagi diliatin juga kalau keduanya sama-sama jalan sama wanita. Kesannya kayak sekedar ketertarikan fisik aja. Padahal lebih dari itu. Elio ngerasa nyambung, sepikiran, dan diapresiasi kalau ngobrol sama Oliver, misalnya waktu Oliver nanya pendapat Elio soal tulisannya.
Biarpun sebisa mungkin menghindari interview yang jelas-jelas judulnya udah mengandung spoiler, sebelum selesai baca bukunya saya udah terlanjur terekspos lumayan banyak spoiler. Salah sendiri juga sih, nontonin interview Armie dan Timmy terus. Hahahaha. Misalnya waktu peach scene, terus monolog ayahnya Elio, dan adegan ending waktu Elio nangis di depan perapian. Ketika tahu filmnya berakhir di situ, sejujurnya saya sedikit kecewa. Ternyata, sang penulis juga sempet ngerasa begitu. Belum selesai baca pun udah banyak pemberitaan soal kemungkinan sekuel dari film ini. Tapi yah namanya juga buku dan film, medianya udah beda banget. Nggak bisa dibandingin. Di film, adaptasinya udah bagus banget. Sementara di buku, saya nggak bisa nangkep kebanyakan dari cultural references yang disebutin, tapi tetap bagus banget juga dan bikin patah hati. :))
“Kamu nangis nonton Call Me by Your Name? Aku juga udah nonton, tapi nggak segitunya ah. Iya sih ending-nya sedih, tapi nggak sampai nangis…” Seorang teman bertanya setelah akhirnya nonton CMBYN juga. Sebelumnya dia pasti udah kenyang dengerin saya ngomongin Armie Hammer.
Saya merasa perlu mengklarifikasi. Hazek. Spoiler dari ending di bukunya nih, siapa tahu kalian nggak mau tahu supaya tetap penasaran pas nonton sekuelnya nanti. Eh tapi, menurut saya baca aja sih. Karena dilihat dari filmnya, adaptasi sekuelnya pun pasti bakalan beda banget.
Okay, last chance to avoid the spoilers.
Yang bikin nangis itu bagian akhir di bukunya. Elio dan Oliver sama-sama tahu kalau mereka pada akhirnya harus berpisah. Mereka cuma bisa bersama di musim panas tahun 1983 itu. Elio pun tahu, Oliver mungkin aja balik ke Italia untuk mampir ke tempat mereka, tapi keadaan nggak akan pernah sama lagi. Waktu Oliver pulang ke AS dan Elio pulang ke rumahnya, ayahnya ngajak dia bicara dan monolognya itu bikin saya terharu. Intinya sang ayah merestui persahabatan atau apapun hubungan anaknya itu dengan Oliver. Dia bilang mereka berdua orang yang baik dan beruntung udah menemukan satu sama lain. Begitu sampai di Amerika, Oliver nelpon ke kediaman Pearlman. Teleponnya sih biasa aja dan dari dialognya saya awalnya merasa masih ada harapan. LDR-an kek gitu. Ternyata nggak juga. Oh iya, ada satu karakter di buku yang sayangnya nggak ada di filmnya seorang anak bernama Vimini, tetangganya Elio. Anak kecil pinter ini sakit leukimia dan tahu kalau waktunya hidup nggak lama lagi. Dia deket banget sama Oliver dan ikutan sedih waktu Oliver balik ke Amerika tanpa pamitan.
Oliver sempat datang ke Italia lagi waktu Natal. Nah, kalau nggak salah di momen ini dia bilang soal rencananya untuk menikah. Waktu baca saya lumayan kaget sih. Kayak… Okay, why didn’t I see that coming? Terus di halaman berikutnya saya sempet kesel banget sama karakternya Oliver. Kok tega sih? Nggak ngomong apa-apa pula, tapi akhirnya ngaku kalau selama dua tahun belakangan hubungannya emang putus nyambung. Kan saya ikutan patah hati… 💔
Elio dan Oliver beberapa kali ketemu lagi berpuluh tahun kemudian. Saya gregetan karena Elio bersikap seakan dia udah bener-bener move on dan menemukan cinta yang lain. Padahal pembaca tahu dia narator yang nggak bisa dipercaya dan cuma Oliver yang benar-benar menghantui kehidupannya. Elio tahu banget sepak terjang Oliver, begitu pun sebaliknya. Oliver pun mengakui kalau hidup yang dia jalani sekarang ini seperti parallel life, kayak kehidupan alternatif gitu. Berarti kan dalam hati sebenarnya ada bagian dari diri Oliver yang berharap dia bisa tetap bersama Elio. Tapi, karena beberapa hal, dia nggak bisa dan harus menjalani kehidupan yang ‘normal’. Aaah pokoknya baca bagian terakhir itu bikin saya nangis sesenggukan di bantal pukul 3 dini hari. SEBEL. Lagu soundtrack-nya yang ‘Mystery of Love’ juga sungguh tidak membantu. Sedih, cuy. Mana setelah selesai baca tuh lagi suka-sukanya lagu ‘Too Good At Goodbyes’ juga. Kebetulan yang menyebalkan.
Nggak lama kemudian saya baru tahu juga kalau CMBYN ada audiobook-nya. Dan naratornya adalah tidak lain dan tidak bukan... Armie Hammer yang cakep, lucu, dan suaranya juga seksi itu. Yep. Seakan lagi menyimak Oliver lagi baca jurnalnya Elio deh pas denger. Saya jadi penasaran nih bakalan kayak gimana kalau bagian akhir bukunya diadaptasi ke film.
Panjang yah... :’)
Suatu hari nanti mungkin saya akan baca ulang bukunya. Dan kalau interpretasi saya berubah, saya kabarin lagi deh ya. Ehehe. Later!
x